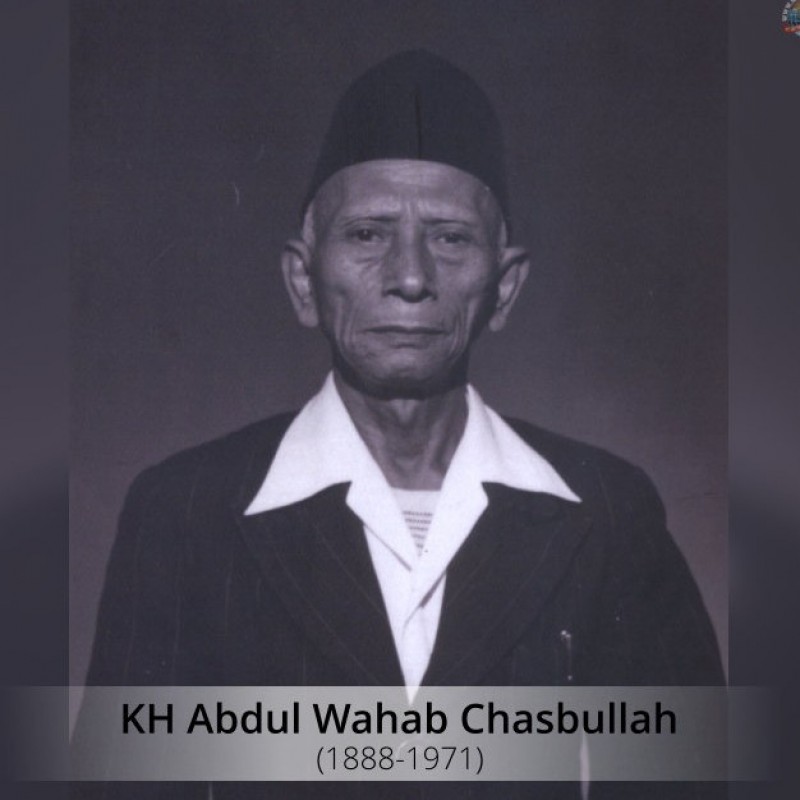Ijtihad Politik KH. Abdul Wahab Hasbullah
KhazanahMuhammad Izzul Islam An Najmi
Mahasiswa Doktor Studi Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
KH. Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang pemimpin pergerakan. Secara aktif, beliau membangun semangat bergerak dikalangan masyarakat, terutama umat Islam tentang harga diri sebagai suatu bangsa. Bersama-sama para pemimpin se-angkatannya beliau ikut merintis pergerakan kemerdekaan Indonesia, dan karena itu mempunyai sumbangan besar dalam mendirikan serta menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Salah satunya terciptanya pluralitas dan kerukunan antar umat beragama. Menurut KH. Saifuddin Zuhri, Kiai Abdul Wahab dilahirkan tahun 1888 di Kampung Tambak Beras, sedangkan versi Greg Fealy dan Greg Barton lain lagi. Kiai Wahab dilahirkan sekitar tahun 1883-1884.
Ijtihad Politik Kiai Abdul Wahab Hasbullah dapat tercemin dalam perjuangannya membentuk Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Tujjar, Komite Hijaz dan NU terlebih kita dapat melihat pengaruh itu dalam diri Kiai Wahab Hasbullah dari nama kelompok diskusi yang ia dirikan sepulang dari Timur Tengah, yakni Tashwirul Afkar, yang diambil dari nama sebuah surat kabar Tasvir-I Efkar, yang berarti ungkapan atau pergolakan pemikiran, yang terbit di Turki pada tahun 1862 pada era Tanzhimat/Reformasi. Surat kabar ini didirikan oleh Ibrahim Sinasi, seorang penyair, reformis Turki yang belajar di Perancis selama revolusi 1848. Ibrahim Sinasi pulang ke Turki membawa ide-ide kebebasan individu, pemerintahan konstitusional, demokrasi perwakilan dan nasionalisme, Sinasi kemudian bergabung dalam gerakan Tanzhimat, gerakan reformasi oleh tokoh-tokoh modernis yang diarahkan terhadap pemerintahan kekhalifahan Turki Utsmani. Demikian pula nama Nahdlatul Wathan. Oleh Kiai Wahab Hasbullah istilah wathan jelas bukan diambil dari khasanah “kitab-kitab kuning” yang terbit pada abad ke-13 yang banyak digunakan di pesantren. Sebagai konsep politik, istilah tersebut baru diperkenalkan menjelang pertengahan abad ke-19, dari khazanah pemikiran kaum modernis Turki Utsmani, yaitu Sadik Rifat Pasya (1807-1856), tokoh penting yang menggelorakan gerakan Tanzhimat. Dalam uraiannya pada apa yang disebut “teori reformasi Tanzhimat”, istilah wathan dalam bahasa Turki disebut vatan dimaknai politis sebagai berarti “wilayah teritorial”, untuk padanan kata partie yang berarti “tanah air” yang juga berarti devlet atau daulah atau “negeri”. Pada perkembangannya, di tangan kalangan pembaharu berikutnya seperti Ziya Gokalp (1876-1924), patriotisme atas dasar vatan dipandang sebagai wilayah moralitas terpenting bagi bangsa Turki, justru pada pengertian teritorial yang lebih terbatas, tidak lagi meliputi Imperium Utsmani. Sementara ketika kekuatan Barat mulai melakukan koloni di sejumlah wilayah Islam, seperti Mesir dan lain-lain, sehingga para pembaharu dituntut melakukan gerakan pembebasan, konsep wathan menemukan energi baru dan bersenyawa dengan konsep syu’ub atau bangsa yang sebelumnya telah dikenal luas oleh masyarakat Islam sehingga konsep itu memperoleh kerangkanya sebagai dasar kenegaraan. Untuk tujuan gerakan pembebasan, akhirnya terbentuklah landasan teologis hubbul wathan minal iman, yang memandang patriotisme sebagai kewajiban suci, sebuah nasionalisme religius.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan sikap kebangsaan serta nasionalisme Kiai Wahab Hasbullah diperoleh melalui jalur yang berbeda dari tokoh-tokoh kebangsaan lainnya, seperti Soekarno, Hatta, dan Soepomo. Kiai Wahab Hasbullah mengenal gagasan nasionalisme dari pergolakan pemikiran yang berkembang di Timur Tengah, sedangkan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Soepomo, mengenal gagasan nasionalisme melalui kontak langsung dengan gagasan-gagasan Barat di sekolah-sekolah Belanda. Hasilnya memang berbeda. Nasionalisme Kiai Wahab Hasbullah bercorak religius sedangkan nasionalisme Soekarno, Hatta dan lainnya bercorak sekuler. Azyumardi Azra Dalam bukunya Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan, menutup pembahasan tentang peran politik NU dengan sebuah teka-teki: Apakah NU pimpinan KH. Abdurrahman Wahid akan kembali pada paradigma yang pernah dikembangkan KH. Abdul Wahab Hasbullah ? Teka-teki itu tidak dijawab, karena teks historis Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memang belum selesai dan masih mungkin mengalami perubahan. Apalagi ketika buku itu ditulis, pengamatan terakhir terhadap Gus Dur hanya sampai pada “aliansi” Gus Dur dengan Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut), dan tentu belum menjadi Presiden RI ke-empat. Dari pertanyaan itu tersirat kesan, Gus Dur akan membawa NU kembali dekat dengan kekuasaan, seperti al-maghfurlah KH. Wahab Hasbullah. Teks religio politik Kiai Wahab memang sudah selesai ditulis dan tidak mengalami “revisi” karena beliau telah wafat. Tetapi benarkah Beliau akomodasionis ? Bagaimana Kiai Wahab “membaca” medan perjuangan, bagaimana ijtihad dan tindakan politiknya bagi pembebasan dan persatuan bangsa.
Perannya di dalam percaturan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariat dalam tradisi keilmuan pesantren. Kiai Wahab mampu mengimbangi aspirasi kelompok Islam lain serta mampu mengendalikan pergerakan kaum sosialis dan komunis di dalam pemerintahan, termasuk saat Presiden Soekarno menggagas integrasi nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom). Keterkaitan rezim orde lama dengan pergerakan Kiai Wahab dalam setiap percaturan dan pergolakan politik dinilai sebagai langkah “politik jalan tengah”. Langkah politik ini tidak mudah dilakukan oleh siapa pun, karena bukan hanya membutuhkan langkah nyata, tetapi juga menuntut argumentasi memadai terkait persoalan yang terjadi. Para kiai NU tersebut selalu mengimbangi konsep PKI dan secara tidak langsung menghalau pikiran-pikiran PKI yang berupaya mengancam keselamatan Pancasila. Kalangan pesantren dan para kiai NU senantiasa mendekat kepada Presiden Soekarno bukan bermaksud “nggandul” kepada penguasa, melainkan agar bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan strategis supaya keputusan-keputusan Soekarno tidak terpengaruh oleh PKI, hubungan baik antara Presiden Soekarno dan Kiai Wahab Hasbullah memudahkan diterimanya saran-saran NU yang disampaikan oleh Kiai Wahab lewat Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) Misalnya, ketika DPAS sedang membicarakan perlu tidaknya berunding soal Irian Barat (sekarang Papua) dengan pihak Belanda, begitu juga saat Kiai Wahab menerima konsep Nasakom Soekarno pada 1960. Ide Nasakom Soekarno terlihat jelas pada Amanat Presiden 17 Agustus 1960 yang kemudian terkenal dengan rumusan “Jalannya Revolusi Kita”.
Dalam pandangan Syaikhul Islam Ali dalam Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama (2018), bagi pengkaji fikih, strategi politik Kiai Wahab tidak salah karena berpijak pada prinsip fikih yang fleksibel dan elastis. Fleksibel tidak dapat disamakan dengan oportunis. Fleksibel mampu masuk di berbagai ruang dengan tetap mempertahankan ideologi, sedangkan oportunis berpihak pada siapa pun asal diberi keuntungan materi. Ketika Bung Karno menyatukan kaum agama, nasionalis, dan komunis dalam bingkai Nasakom, Kiai Wahab mendukung konsep tersebut dengan cara bergabung dalam sistem pemerintahan. Komitmen Kiai Wahab dan ulama-ulama pesantren tidak berubah terhadap gerak-gerik PKI dengan komunismenya, yaitu tetap melawan dan menentang karena ideologi politik PKI bertentangan dengan prinsip Pancasila. Sebab itu, Kiai Wahab memilih bergabung dalam Nasakom bertujuan untuk mengawal kepemimpinan Bung Karno supaya perjalanan pemerintahan tetap bisa dikendalikan oleh NU sebagai perwakilan umat Islam dan tidak dimonopoli oleh PNI atau pun PKI. Ditegaskan oleh Kiai Wahab, untuk mengubah kebijakan pemerintahan tidak bisa dengan berteriak-teriak di luar sistem, tetapi harus masuk ke dalam sistem. Kalau Cuma berteriak-teriak di luar, maka akan dituduh makar atau pemberontak. Prinsip dan kaidah yang dipegang oleh Kiai Wahab dalam tataran fikih ialah, kemaslahatan bergabung dengan Nasakom lebih jelas dan kuat daripada menolak dan menjauhinya, taqdimul mashlahatir rajihah aula min taqdimil mashlahatil marjuhah (mendaulukan kemaslahatan yang sudah jelas lebih didahulukan dari kemaslahatan yang belum jelas). Karena jika tidak ada NU sebagai perwakilan Islam, PKI akan lebih leluasa mempengaruhi setiap kebijakan Soekarno.
Karakter Islam Indonesia adalah wasathiyah yaitu berada di tengah-tengah. Tradisi mainstream muslim Indonesia adalah karakter washatiyah dengan menekankan tawazun dan i’tidal seperti yang dicerminkan oleh Muhammadiyah dan NU. Hal ini nampak dari sikap NU ketika masuk dalam ide Nasakom Bung karno, sesumbar Kiai Abdul Wahab Hasbullah, tampaknya tidak sekadar isapan jempol. Pemilu 1955 yang oleh kalangan pemerhati dinilai berlangsung demokratis, jujur dan transparan, berhasil mengantarkan NU masuk dalam empat partai besar, yaitu PNI dengan jumlah suara 8,5 juta suara (22,396), Masyumi dengan 8 juta suara (20,996), NU dengan 7 juta suara (18,496) persen dan PKI dengan 6,1 juta suara (16,496). Ke-empat partai ini secara berturut-turut mendapat 57, 57, 45 dan 39 kursi di parlemen. Jumlah keseluruhan peroleh kursi keempatnya adalah 198 dari 257 kursi. Sisanya, 59 kursi terbagi di antara partai-partai kecil, Kecuali menjadi anggota DPR hasil Pemilu 1955, KH. Wahab Hasbullah juga menjadi anggota Majelis Konstituante. Sesuai dengan UU Pemilu 1955 Konstituante bertugas menyusun Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, UUD yang berlaku saat itu (UUD Sementara 1950) akan diganti dengan UUD hasil Konsituante.
Sebelumnya Indonesia telah mempunyai UUD 1945. Dalam Konstituante, kalangan Islam kembali memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, namun mengalami kebuntuan, hingga akhirnya keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Konstituante hasil Pemilu 1955 dibubarkan. Sebelumnya Kabinet-Ali, hasil pemilihan, juga tidak dapat bertahan lama karena adanya pertikaian antara Masyumi dan PNI menyangkut konsep hubungan pemerintah pusat dan daerah. Masyumi akhir nya menarik para menterinya sehingga Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada 14 Maret 1957. Pada Saat itu juga diberlakukan keadaan bahaya sehingga pihak militer mulai menentukan keluarnya Dekrit 5 Juli 1959 menandai menguatnya dominasi kekuasaan Soekarno Antara 1955 dan 1965 dapat dikatakan periode Soekarno Presiden konstitusional pada masa ini sering menyatakan keinginannya untuk lebih dari sekadar simbol dan ingin menentukan jalannya pemerintahan. Pada 20 Juli 1956 Mohammad Hatta mengirimkan surat resmi pengunduran dirinya kepada DPR sebagai wakil presiden karena kecewa terhadap kinerja parlemen yang tidak berwibawa, pemerintah yang tidak mengutamakan pembangunan kesejahteraan rakyat dan Presiden Soekarno yang sering bertindak ekstra konstitusional. Rezim kekuasaan Soekarno tampak lebih nyata ketika dia menyatakan keinginannya hendak mengubur partai-partai dan menganggap perlunya Dewan Nasional yang akan dipimpinnya secara langsung. Soekarno memanggil semua pemimpin partai, termasuk Masyumi untuk meminta pandangan mereka tentang gagasan tersebut. Pada saat itu pimpinan Masyumi menyampaikan keberatannya, namun Soekarno jalan terus.
Pada 14 Maret 1957 Soekarno menunjuk Suwirjo dari PNI sebagai formatur untuk menyusun pembentukan Dewan Nasional. Masyumi tidak diajak formatur dalam kabinet. Tapi penyusunan ini gagal karena partai-partai agama lain menolak calon-calon dari PKI. Lalu Presiden memerintahkan untuk membentuk zaken kabinet darurat. Parlemen hasil pemilu 1955 sampai Maret 1960 masih bekerja, tetapi pada bulan itu dibubarkan, dan Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Presiden tidak mengikutsertakan Masyumi, dan karena beberapa tokoh Masyumi seperti Mohammad Nasir dan Sjafruddin Prawiranegara pada 1958 membentuk PRRI, Masyumi diminta membuktikan keterlibatannya karena gagal dalam pembuktian itu, Presiden Soekarno memerintahkan pembubaran Masyumi pada 17 Agustus 1960. Banyak tokoh Masyumi yang terlibat dalam PRRI dipenjarakan, yang menarik, sikap tokoh-tokoh NU dalam merespon proses rezimentasi kekuasaan Soekarno ternyata tidak semua akomodatif, sehingga menimbulkan faksi politik garis keras (hardliner) di dalam organisasi alam ini. KH. Mohammad Dahlan, yang waktu itu mendampingi Rais Am KH. Wahab Hasbullah sebagai Wakil Ketua I Syuriah NU, misalnya, justru menolak duduk di dalam keanggotaan DPR-GR. Alasannya, selain tidak demokratis, lembaga ini dibentuk tanpa melalui pemilu, dan meniadakan kekuatan oposisi. Keberanian Dahlan tidak hanya itu. Sebelumnya, pada tahun 1956 ketika Soekarno memerintahkan agar dibentuk kabinet koalisi yang terdiri kalangan nasionalis, agama dan marxis, yang lebih dikenal dengan sebutan Nasakom. KH. Mohammad Dahlan, secara terang-terangan menentang gagasan itu. Bahkan, beliau bersama-sama dengan KH. Imron Rosyadi mendirikan Liga Demokrasi. Liga yang memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh seperti Cosmas Batubara, Napitupulu dan Silalahi ini, menentang Nasakom khususnya dan Demokrasi Terpimpin pada umumnya. Demikian pula ketika terjadi krisis politik akibat meletusnya G30S/PKI, KH. M. Dahlan termasuk tokoh NU yang mengutuk keras gerakan tersebut. Dan, bersama Subhan, dia mendirikan Front Pancasila sebagai counter atas Front Nasional-nya Bung Karno.
Namun artikulasi yang dilakukan sayap politik NU garis keras di atas, seperti terlihat dalam sejarah NU, tampak kurang mampu mengimbangi mainstream politik NU secara keseluruhan yang dikembangkan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Dalam perjuangannya Kiai Wahab masuk nasakom karena itu salah satu upaya untuk mempertemukan Islam dan nasionalisme. Kiai Wahab mengatakan “masuk dulu, keluar gampang”. Beliau menggunakan segala cara untuk melawan Penjajahan dan dalam mengupayakan Islam dan Negara bahkan sampai ada cerita pada waktu Indonesia masih dijajah dulu, ada sebuah kejadian ketika Mbah Wahab dan rombongan akan diserbu dan dihadang oleh tentara Belanda melalui jalur udara dengan mengendarai pesawat. Melihat pesawat tersebut, Mbah Wahab langsung mengambil batu kemudian dibungkus dengan sorbannya dan dilemparkan ke arah pesawat, Seketika pesawat tersebut langsung oleng. Cerita-cerita unik tersebut terkadang memang susah dinalar tapi memang terjadi. Bukankah tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki.
Demikianlah Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ulama yang diberkati Tuhan memperoleh kesempatan hidup dalam tiga zaman. Pertama, zaman pergerakan kemerdekaan. Kedua, sesudah proklamasi kemerdekaan dan ketiga, masa Orde Baru. Kiai ini pernah merasakan pahit getirnya hidup, dan banyak teladan yang ditinggalkan bagi generasi sesudahnya. Dalam masa kepemimpinannya beliau juga tidak lepas dari ejekan, fitnah dan hinaan disamping tentu saja sanjungan dan hormat. Pada zaman Orde Lama misalnya. banyak orang mengejek Kiai Wahab sebagai “Kiai Nasakom” atau “Kiai Orla” lantaran NU menerima konsep Nasakom dan dekat dengan Bung Karno. Menanggapi hal ini Kiai Wahab berjiwa besar dan menanggapi dengan tertawa enteng. “Ha..ha.. ha.. Ya biarkan saja,” katanya. “Ejekan itu masih belum apa-apa dibanding dengan ejekan terhadap Nabi Muhammad saw. yang dianggap gila. Saya kan masih belum dianggap gila,” katanya, yang jelas, hampir sepanjang hidupnya, dicurahkan untuk mewujudkan cita-cita Islam dan bangsa.
Tidak heran jika Kiai Wahab tidak pernah absen selama 25 kali Muktamar NU. Saat sakit, Kiai Wahab masih berkeinginan bisa menghadiri Muktamar ke 25 di Surabaya dan sekali lagi dalam Muktamar ini beliau terpilih sebagai Rais Aam PBNU. Dalam khutbah iftitahnya yang terakhir sebagai Rais Aam (yang dibacakan Kiai Bisri Syansuri), Kiai Wahab masih sempat berharap, “Supaya NU tetap arah jalannya melalui cara-cara yang sesuai dengan akhlak ahlussunnah wal jama’ah”. Salah satu karya tulis beliau yang sudah ditemukan adalah kitab Penyerap gemuruh atau ada juga yang menyebut penyirep gemuruh, yang membahas permasalahan perluasan Masjid Jami’ Peneleh Surabaya yang menggunakan tanah kuburan. Beberapa pandangan dan isi pemikiran Kiai Wahab juga terlihat dalam kitab tersebut seperti pandangan beliau dengan menyamakan tanah kuburan yang statusnya sudah tidak bisa digunakan dan tidak dapat diharapkan untuk menguburkan lagi, Kiai Wahab menghukumi tanah itu, tanah yang tidak teridentifikasi (majhula), kemudian tanah tersebut dapat disamakan hukumnya dengan harta yang tersia-sia (mallun dhoiun). Hal ini membuktikan bahwa basis pemikiran beliau adalah fikih dengan pendekatan integrasi keilmuan.
Keluwesan Kiai Wahab juga dapat dilihat dalam kitab penyerap gemuruh, yakni ketika beliau membolehkan membongkar kuburan untuk keperluan perluasan masjid, redaksi dalam kitabnya yakni “diperbolehkan menggali kuburan yang belum diketahui tentang jelasnya informasi kuburan tersebut kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Hal ini seperti kaidah fikih (lianna dhorurot tubikhu mahdhuroh) adapun contoh keadaan darurat yakni seperti mengambil cicin yang ikut terpendam ketika menguburkan mayit walaupun mayit didalam kuburannya belum menjadi tulang”. Demikianlah keluwesan Kiai Wahab bahwa sesuatu yang tidak dibolehkan juga dapat menjadi boleh tergantung situasi dan kondisi yang menyertainya.