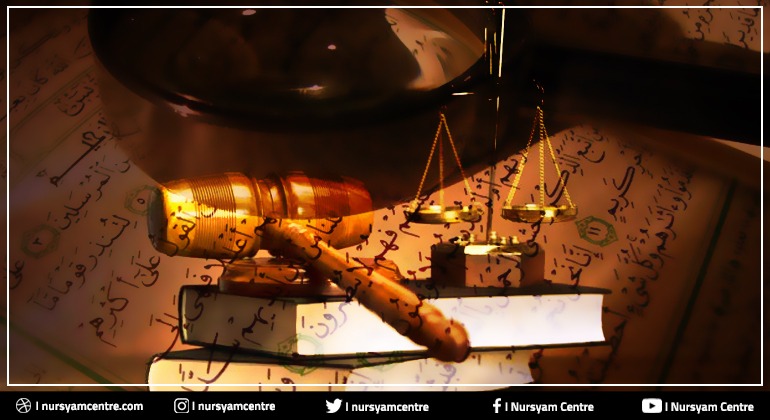Sabab al-Nuzul dan Penetapan Hukum
Daras TafsirDengan mengharap rida Allah SWT dan ilmu yang bermanfaat dan berkah, mari sejenak membaca surah al-Fatihah kepada penulis kitab Zubdat al-Itqan yang sedang kita kaji bersama. Untuk Abuya al-Sayyid Muhammad b. ‘Alwi al-Maliki, al-Fatihah.
Pendahuluan
Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas urgensi Sabab al-Nuzul dalam memahami pesan yang terkandung dalam sebuah ayat. Di sini kita akan melangkah lebih jauh. Bahwa ketika kita telah memahami Sabab al-Nuzul sebuah ayat dan ayat tersebut mengandung hukum syariat, pertanyaannya, apakah hukum itu hanya berlaku khusus bagi “sebab” yang melatarbelakanginya, atau sebaliknya, berlaku umum bagi “yang lain”? Ini merupakan salah satu persoalan penting terkait Sabab al-Nuzul yang dibahas oleh para ulama bidang Ushul. Persoalan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini.
Pembahasan
Mayoritas ulama menjawab pertanyaan di atas dengan sebuah ungkapan yang belakangan menjadi adagium dalam persoalan ini. Yakni bahwa, “Yang dijadikan patokan adalah keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab (al-‘Ibrah bi ‘umum al-lafzh la bi khushush al-sabab).” Oleh karenanya, hukum yang terkandung dalam sebuah ayat yang turun dalam konteks spesifik itu juga berlaku bagi konteks-konteks yang lain. Dengan kata lain, meskipun hukum syariat itu tertuju pada “sebab khusus”, tetapi berhubung ayatnya beredaksi umum, ia juga diberlakukan pada persoalan-persoalan lain yang serupa.
Pada konteks ini, al-Hafizdh Jalal al-Din al-Suyuthi berkata, “Di antara dalil yang menunjukkan dijadikannya keumuman redaksi sebagai patokan adalah argumentasi para sahabat RA, dalam berbagai peristiwa, dengan berpedoman pada keumuman ayat-ayat yang—notabene—turun dalam sebab-sebab spesifik. Hal ini menjadi ketetapan yang berlaku secara luas di kalangan mereka.” Ada banyak contoh yang disebutkan oleh para ulama terkait hal ini. Tetapi kita akan fokus pada 3 contoh yang disebutkan oleh Abuya dalam Zubdat al-Itqan-nya. Pertama, ayat al-zhihar, yakni surah al-Mujadalah ayat pertama berikut ini:
Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang mendebatmu tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar diskusi kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Imam al-Suyuthi dalam Lubab al-Nuqul-nya menuliskan sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan Aus b. al-Shamit yang men-zhihar istrinya, Khaulah bint Tsa‘labah. Kemudian Khaulah mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, “Ya Rasulallah, dia—maksudnya Aus b. al-Shamit, suaminya—telah menghabiskan masa mudaku, dan aku pun telah menyerahkan “perutku” untuknya. Hingga saat usiaku telah lanjut (tak lagi muda) dan tak lagi mampu melahirkan, dia men-zhihar-ku. Ya Allah, sungguh aku mengadu kepada-Mu.” Tak berselang lama, turunlah Jibril AS menyampaikan ayat di atas—dan beberapa ayat setelahnya—kepada Rasulullah SAW.
Baca Juga : Anti Terorisme: Sebaiknya Dengan Gerakan Preventif
Yang patut digarisbawahi di sini adalah hukum yang terkandung pada ayat-ayat zhihar. Di sana disebutkan bahwa solusi atas persoalan zhihar ialah si suami harus memerdekakan seorang budak sebelum ia “bersentuhan” dengan istrinya. Kalau ia tidak mampu, maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut—dengan hitungan qomariyah, bukan syamsyiah. Kalau masih tidak mampu karena satu dan lain alasan yang dapat dibenarkan, maka wajib memberi makan enam puluh orang miskin; setiap orang miskin diberi satu porsi makanan yang mengenyangkan.
Nah, sejarah membuktikan bahwa para ulama—bahkan Rasulullah SAW—juga memberlakukan hukum zhihar itu kepada suami-suami yang men-zhihar istrinya dan hendak “merujuknya” kembali. Tegasnya, pemberlakuan hukum zhihar itu tidak terbatas pada Aus b. al-Shamit saja sebagai “sebab” turunnya ayat-ayat zhihar, tetapi juga diberlakukan pada persoalan-persoalan yang serupa. Salamah b. Shakr RA misalnya, beliau pernah mengalami hal serupa tetapi dengan motif yang sedikit berbeda, sebagaimana terekam dalam sebuah riwayat berikut ini:
Telah masuk bulan Ramadhan. Aku takut “mengenai” istriku (di siang hari bulan Ramadhan), maka aku pun men-zhihar-nya, hingga Ramadhan berlalu. Pada suatu malam, sesuatu tersingkap darinya, maka aku pun “mengenainya”. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Bebaskanlah seorang budak.” Aku menjawab, “Aku tak punya apa-apa selain diriku.” Beliau bersabda, “Maka berpuasalah dua bulan berturut-turut.” Aku menjawab, “Bukankah aku tidak melakukan demikian itu melainkan karena puasa?” Beliau bersabda, “Berilah makan satu wasaq kurma kepada enam puluh orang miskin.” (HR Ahmad, al-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibn Majah, dan dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah, Ibn al-Jarud dan al-Hakim) [1 wasaq = 60 sha’ = 103.680 gram menurut perkiraan Imam al-Nawawi]
Kedua, ayat al-li‘an, yakni surah al-Nur ayat 6 berikut ini:
Dan orang-orang yang menuduh istri mereka, padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka ialah empat kesaksian dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.
Ayat ini turun berkenaan dengan Hilal bin Umayyah yang menuduh di hadapan Nabi SAW bahwa istrinya menyeleweng. Nabi SAW menuntut bukti darinya—yakni empat orang saksi—atau dicambuk—jika tidak dapat memenuhi. Hilal berkata, “Ya Rasulallah, jika salah seorang dari kita melihat istrinya bersama lelaki lain, masihkah butuh bukti?” Nabi SAW tetap bersabda, “(Datangkanlah) bukti atau cambukan di punggungmu.” Hilal berkata, “Demi Dzat yang mengutus engkau dengan haq, sungguh aku benar dan sungguh Allah akan menurunkan ayat yang membebaskan punggungku dari cambukan.” Maka Allah SWT menurunkan ayat di atas kepada Nabi SAW.
Sebagaimana persoalan zhihar, persoalan menuduh istri telah menyeleweng di sini ada konsekuensinya. Yakni, bila suami tidak mempunyai saksi, maka dia bersumpah empat kali bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Lalu ditambah sumpah kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk para pembohong. Apabila sang istri diam, tidak membantah tuduhan suami, maka sang istri dijatuhi sanksi hukum zina. Tetapi bila sebaliknya, maka sang istri harus melakukan hal yang serupa. Yakni bersumpah empat kali, bahwa suaminya benar-benar termasuk para pembohong. Lalu ditambah sumpah kelima, bahwa murka Allah atasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar. Nah, prosedur ini terbukti ditetapkan bagi siapa pun yang menuduh istrinya telah menyeleweng. Ia tidak hanya berlaku bagi Hilal b. Umayyah dan istrinya saja.
Baca Juga : Niali-Nilai Pesantren Pada Era Disruptif (Bagian Kedua)
Ketiga, hukuman qadzaf bagi para penuduh Umm al-Mu’minin ‘Aisyah RA. Kita tahu bahwa beliau pernah dituduh telah berbuat menyeleweng dengan Shafwan b. al-Mu‘aththil al-Sulami, salah seorang sahabat yang paling terdahulu memeluk Islam dan terlibat juga dalam Perang Badr bersama Nabi SAW. Singkat kata, tuduhan yang menyebar luas dan menghebohkan bagaikan api dalam sekam itu, pada akhirnya direspon oleh Al-Qur’an dengan turunnya surah al-Nur ayat 11-20. Nah, meskipun para ulama berbeda pendapat apakah hukuman qadzaf diterapkan atas mereka yang terlibat dalam tuduhan itu atau tidak, tetapi mereka sepakat bahwa hukuman itu juga berlaku bagi persoalan-persoalan yang serupa. Yakni dicambuk delapan puluh kali.
Sampai di sini, mari kembali pada persoalan awal. “Bagaimana dengan mereka yang tidak menjadikan keumuman lafadz sebagai patokan? Apakah itu berarti mereka menganggap bahwa ayat-ayat itu hanya berlaku khusus bagi “sebab-sebab” yang melatarbelakanginya?” Jawabannya, tidak. Mereka tetap memberlakukan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat beredaksi umum itu pada persoalan-persoalan lain, tetapi patokannya adalah dalil lain, bukan keumuman lafadz itu sendiri. Dari sini, muncullah adagium baru, “Yang dijadikan patokan adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafadz (al-‘Ibrah bi khushush al-sabab la bi ‘umum al-lafzh).” Artinya, ayat-ayat beredaksi umum itu tetap dipahami sebagai ayat-ayat yang berkaitan dengan sebab-sebab khusus. Adapun pemberlakukan hukum yang dikandungnya pada persoalan-persoalan lain serupa, tidak dilakukan secara serta-merta dengan berdalih “keumuman redaksi”. Tetapi, pemberlakukannya didasarkan pada “dalil lain”.
Kekhususan Sebab + Kekhususan Redaksi
Semua yang telah dijelaskan di atas adalah berkaitan dengan ayat-ayat beredaksi umum yang memiliki sebab khusus. Nah, di sini Abuya menggarisbawahi lebih lanjut, bahwa ayat yang turun dalam konteks spesifik dan tidak ada keumuman sama sekali dalam redaksinya, maka ia hanya berlaku bagi konteks spesifik tersebut. Contohnya, surah al-Lail ayat 17-18 berikut ini:
Dan akan dijauhkan darinya orang yang paling takwa yang menafkahkan hartanya untuk membersihkan.
Ayat ini disepakati oleh para ulama turun berkenaan dengan sahabat Abu Bakar al-Shiddiq RA. “Ada sementara orang yang menduga bahwa ayat ini berlaku umum bagi siapa saja yang beramal seperti beliau; memberlakukannya sesuai kaidah di atas—yakni tentang keumuman lafazh. Dugaan ini salah, karena ayat ini tidak mengandung redaksi umum sama sekali. Karena alif lam (al ta‘rif) itu berfaedah umum hanya bila berposisi sebagai maushul, mu‘arrifat fi jam‘, atau—sebagian ulama menambahkan—mu‘arrifat fi mufrad dengan syarat tidak ada ‘ahdun di sana. Nah, sedangkan lam yang terdapat dalam al-atqa itu bukanlah maushul, karena al tidak bisa bersambung dengan af‘al al-tafdhil, menurut kesepakatan ulama; dan al-atqa juga bukan jamak, tetapi mufrad dan al-‘ahdu-nya ada, apalagi makna al-tamyiz (pembedaan/pengistimewaan) dan qath‘ al-musyarakah (memutus adanya keterlibatan pihak lain) yang terkandung dalam shighat af‘al itu. Dengan demikian, gugurlah pendapat yang mengatakan bahwa ayat di atas beredaksi umum, dan jelaslah bahwa ia hanya berlaku bagi orang yang melatarbelakangi turunnya ayat itu—yakni sahabat Abu Bakar al-Shiddiq—radhiyallahu ‘anhu,” demikian kurang lebih penjelasan Abuya sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Suyuthi dalam al-Itqan-nya.
Catatan
(*) Yang dimaksud dengan zhihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku.” Pada masa itu, ucapan ini dinilai sebagai ucapan yang mengandung makna majas (metaforis) yang berarti bahwa istri tidak lagi halal untuk digauli, tetapi dalam saat yang sama, ucapan ini bukanlah perceraian sehingga istri tidak dapat kawin dengan pria lain.
Baca Juga : Diperlukan Institusi Bersinar: Gerakan PTKIN Bersih Narkoba
(**) Tuduhan tidak berdasar yang dialamatkan pada Umm al-Mu’minin ‘Aisyah RA dan Shafwan b. al-Mu‘aththil al-Sulami di atas, masyhur disebut sebagai Hadits al-Ifki (Berita/Peristiwa Kebohongan Besar). Peristiwa itu terjadi saat kepulangan beliau berdua dari pertempuran Bani al-Mushthaliq. Adapun orang yang mengambil inisiatif dan berperan besar dalam penyebaran berita bohong itu adalah ‘Abdullah b. Ubay b. Salul, tokoh kaum munafik.
Sumber Rujukan
Jalal al-Din b. ‘Abd al-Rahman al-Suyuthi, Asbab al-Nuzul al-Musamma Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul (Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah, 2002), 181-182, 255.
____________, al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an (Kairo: Dar al-Salam, 2013), Vol. 1, 88-90.
Al-Sayyid Muhammad b. ‘Alwi al-Maliki, Zubdat al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an (Madinah: Mathabi‘ al-Rasyid, t.t.), 20-21.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Tangerang: Lentera Hati, 2017), Vol. 13, 463, 467, 473-475, Vol. 8, 482-486, 490-495, Vol. 15, 368-369.
Nur al-Din ‘Itq, I‘lam al-Anam: Syarh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam (Damaskus: Dar al-Farfur, 1999), Vol. 3, 519-522.
Al-Imam Ibn al-Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar (Dammam: Dar Ibn al-Jawzi, 1421 H), 370.